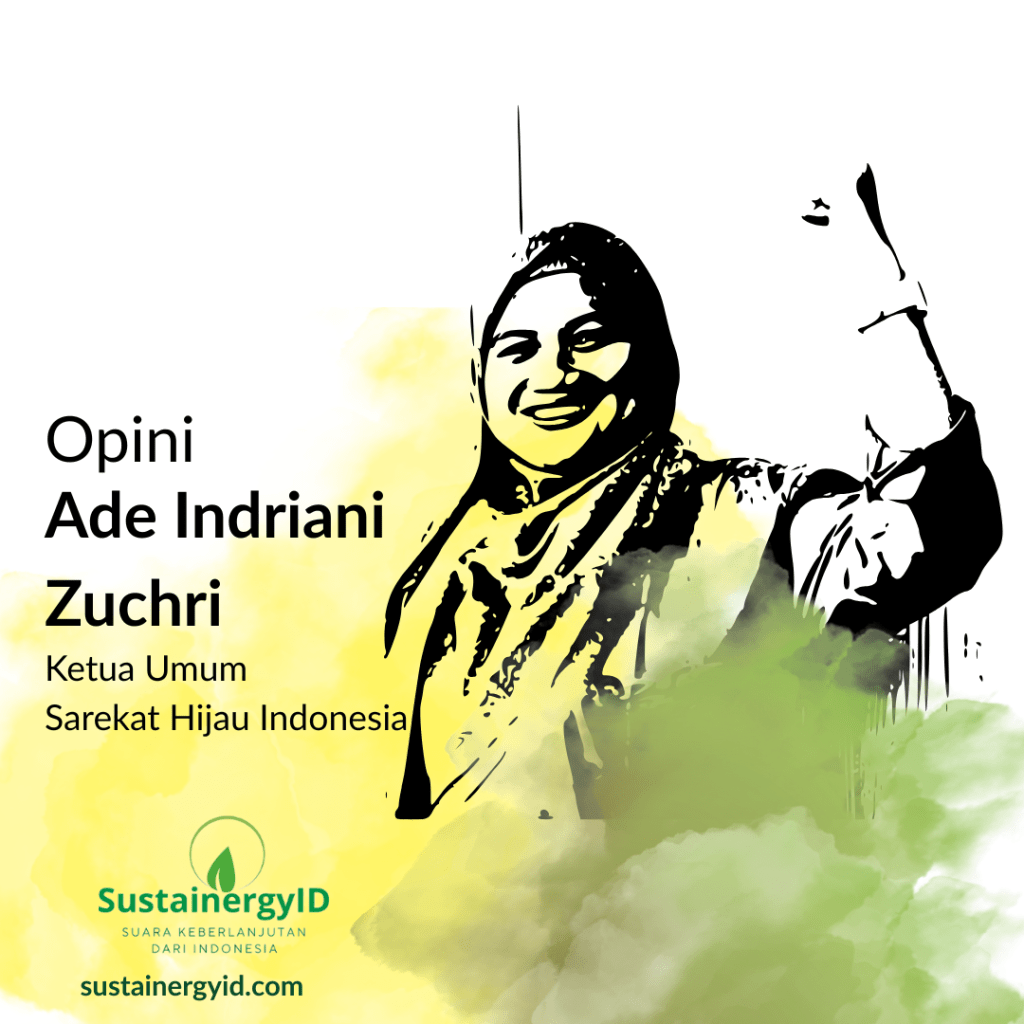
Sumatera Selatan merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam, termasuk hutan primer, lahan gambut, mineral, dan potensi agraris yang luas. Kekayaan ini menghadirkan peluang ekonomi yang signifikan, namun sekaligus menimbulkan risiko ekologis, sosial, dan gender yang kompleks.
Dalam dua dekade terakhir, tekanan terhadap sumber daya alam meningkat secara tajam akibat konversi hutan untuk perkebunan skala besar, pertambangan batubara dan mineral, serta praktik pembukaan lahan yang tidak berkelanjutan.
Fenomena ini tidak hanya menyebabkan degradasi lingkungan tetapi juga mengancam keanekaragaman hayati, mengurangi potensi ekonomi agraris masyarakat lokal, dan memperkuat ketimpangan sosial, terutama bagi perempuan yang mayoritas berperan dalam sektor produksi pangan dan pengelolaan sumber daya rumah tangga.
Deforestasi dan degradasi lahan gambut di Sumatera Selatan telah menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai flora dan fauna endemik, termasuk spesies yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi penting, seperti sagu, purun, ikan air tawar, dan tumbuhan obat tradisional.
Kehilangan keanekaragaman hayati ini berdampak langsung terhadap ekonomi lokal, karena masyarakat agraris yang sebagian besar bergantung pada pertanian skala kecil, perikanan, dan pengumpulan hasil hutan non-kayu mengalami penurunan produktivitas dan pendapatan.
Dalam banyak komunitas, perempuan memainkan peran sentral dalam pengelolaan lahan, produksi pangan, pengolahan hasil hutan, dan usaha rumah tangga yang bergantung pada sumber daya alam. Degradasi lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati secara tidak proporsional meningkatkan beban kerja perempuan, mengurangi akses mereka terhadap bahan pangan dan sumber pendapatan, serta mempersempit kesempatan partisipasi ekonomi.
Potensi bencana di masa depan di Sumatera Selatan dapat diprediksi melalui tren kerusakan ekosistem dan praktik pengelolaan lahan saat ini. Banjir di dataran rendah kemungkinan akan meningkat frekuensi dan intensitasnya akibat sedimentasi sungai yang dihasilkan dari erosi hulu, sementara kebakaran lahan gambut dapat menjadi lebih parah seiring meluasnya lahan terdegradasi. Wilayah perbukitan yang mengalami deforestasi rentan terhadap longsor, terutama jika pembangunan infrastruktur dilakukan tanpa mempertimbangkan geologi dan risiko lereng. Dampak kumulatif dari kombinasi bencana ini akan menurunkan ketahanan pangan lokal, mengganggu mata pencaharian agraris, dan memperdalam kemiskinan struktural.
Perempuan, sebagai pengelola rumah tangga dan produsen pangan lokal, akan menghadapi dampak ganda: harus menanggung kehilangan sumber pangan, beradaptasi terhadap risiko kesehatan, dan mengelola pemulihan ekonomi keluarga di tengah keterbatasan akses terhadap sumber daya dan bantuan.
Pembelajaran dari bencana terbaru di provinsi lain di Sumatera menjadi sangat relevan. Pada akhir 2025, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami bencana hidrometeorologi besar akibat curah hujan ekstrem, dengan dampak parah berupa banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur. Ribuan rumah terendam, akses transportasi terputus, dan layanan dasar terganggu. Analisis dari perspektif resource curse menunjukkan bahwa penyebab parahnya dampak bukan semata-mata ekstrem cuaca, tetapi diperparah oleh degradasi lingkungan: konversi lahan hulu, deforestasi, dan pengelolaan lahan yang buruk.
Kekayaan sumber daya alam yang seharusnya menjadi modal pembangunan justru menjadi faktor risiko karena tidak dikelola secara inklusif dan berkelanjutan. Ketergantungan ekonomi masyarakat lokal pada produksi agraris skala kecil membuat mereka paling terdampak, terutama perempuan yang memiliki tanggung jawab dominan dalam pengelolaan lahan dan rumah tangga, sementara perizinan yang tumpang tindih untuk perkebunan dan pertambangan memperkuat pola resource grabbing dan memperbesar kerentanan ekologis serta sosial.
Kondisi serupa terlihat di Aceh, di mana praktik ekstraktif dan ekspansi perkebunan memperparah risiko banjir. Sumatera Utara, dengan deforestasi di wilayah hulu, memperlihatkan hubungan langsung antara pengelolaan lahan dan banjir di hilir. Sementara itu, Sumatera Barat menghadapi risiko longsor di lereng bukit akibat pembangunan infrastruktur dan permukiman yang tidak adaptif terhadap kondisi geologi.
Fenomena ini menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam, jika tidak dikelola secara berkelanjutan, dapat menjadi sumber bencana dan memperlihatkan inti dari teori kutukan sumber daya: sumber daya yang melimpah, tanpa tata kelola yang adil dan berkelanjutan, dapat memicu kerentanan ekologis, sosial, ekonomi, dan gender.
Dalam konteks Sumatera Selatan, pengalaman 2025 di Aceh, Sumut, dan Sumbar menjadi peringatan penting. Potensi bencana yang muncul akibat curah hujan ekstrem, konversi lahan, deforestasi, dan degradasi lahan gambut dapat diantisipasi melalui penguatan tata kelola sumber daya alam. Reformasi perizinan, moratorium di ekosistem kritis, penerapan peta risiko berbasis spasial, dan konsultasi dengan komunitas lokal menjadi langkah penting. Restorasi ekosistem hulu, proteksi lahan gambut, dan zonasi wilayah berisiko dapat mencegah banjir, longsor, dan kebakaran lahan. Diversifikasi mata pencaharian masyarakat melalui agroforestry, ekowisata, dan budidaya tanaman lokal yang berkelanjutan meningkatkan kapasitas adaptif dan mengurangi tekanan terhadap lahan.

Upaya ini secara langsug mendukung pemberdayaan perempuan, dengan memberikan akses lebih besar terhadap sumber pendapatan, bahan pangan, dan peran dalam pengambilan keputusan komunitas. Sistem peringatan dini, pelatihan kesiapsiagaan, dan mekanisme respons cepat menjadi instrumen utama pengurangan risiko bencana. Transparansi, penegakan hukum, dan partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya mengurangi praktik perampokan sumber daya dan memperkuat keadilan lingkungan dan gender. Skema pembiayaan adaptasi, kredit iklim, dana adaptasi daerah, dan pembayaran jasa ekosistem dapat mendukung konservasi dan mitigasi risiko secara berkelanjutan.
Dari perspektif sosial-ekonomi dan gender, masyarakat agraris di Sumatera Selatan, yang bergantung pada produksi pertanian skala kecil dan hasil hutan non-kayu, sangat rentan terhadap bencana. Kehilangan lahan produktif, degradasi ekosistem, dan hilangnya keanekaragaman hayati mengurangi ketahanan pangan lokal, pendapatan rumah tangga, dan kesejahteraan perempuan.
Oleh karena itu, kebijakan mitigasi bencana harus mengintegrasikan aspek ekologis, ekonomi, sosial, dan gender secara holistik, menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh anggota masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan adaptif memungkinkan Sumatera Selatan untuk memanfaatkan kekayaannya sebagai modal pembangunan, bukan sebagai kutukan ekologis, sosial, maupun gender.
Dengan menggabungkan pembelajaran empiris dari Aceh, Sumut, dan Sumbar 2025 serta analisis teori resource curse, strategi adaptif untuk Sumatera Selatan dapat dikembangkan. Pendekatan ini menuntut komitmen politik yang kuat untuk mengalihkan insentif ekonomi dari eksploitasi cepat menuju pembangunan berkelanjutan, penguatan kapasitas adaptif masyarakat, perlindungan ekosistem kritis, pemberdayaan perempuan, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya.
Hanya melalui strategi yang terpadu dan berbasis bukti, Sumatera Selatan dapat mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketahanan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
***
Ade Indriani Zuchri, Ketua Umum Sarekat Hijau Indonesia.





Tinggalkan komentar