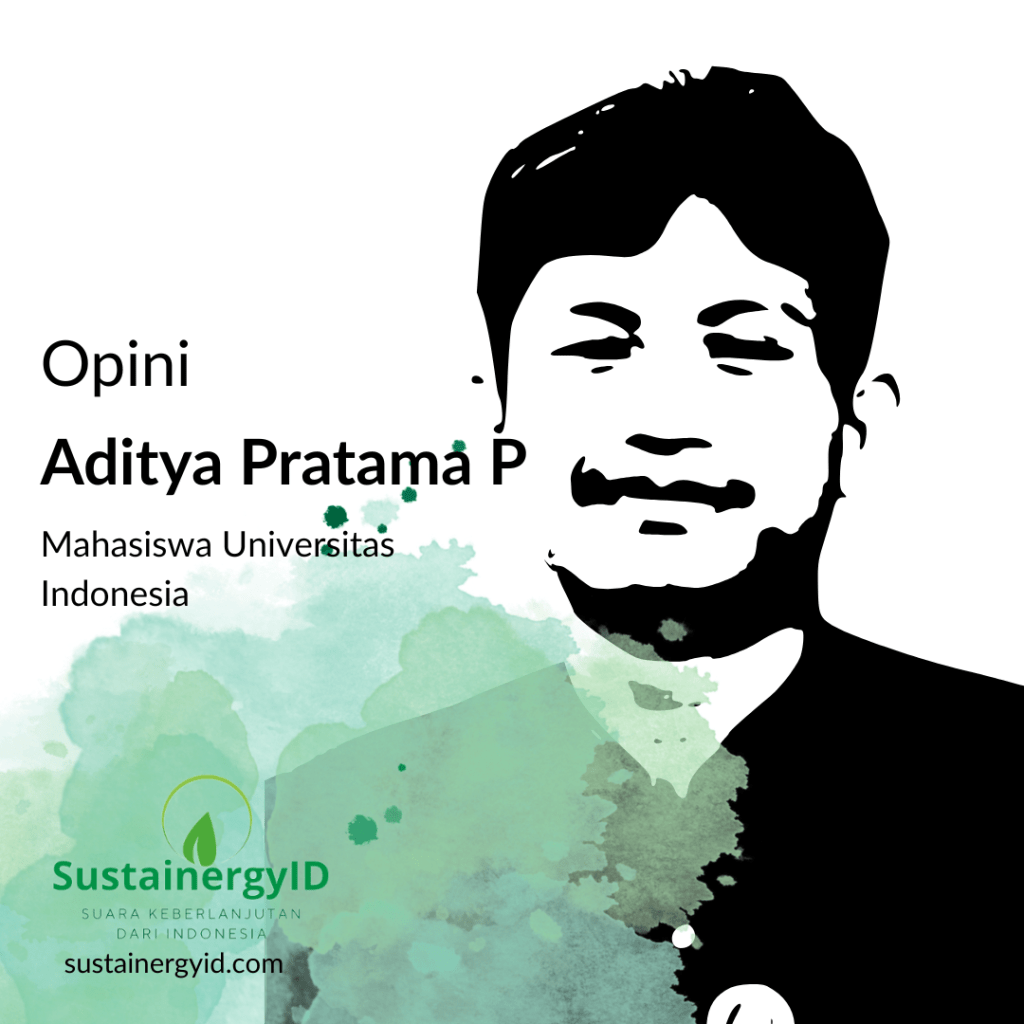
“To protect the forest is to protect relationships, between humans and nature.”
— Winona LaDuke
Perubahan iklim global menempatkan hutan tropis sebagai salah satu benteng terakhir dalam menekan emisi karbon. Indonesia, dengan luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia, memegang peran strategis. Namun, fakta menunjukkan bahwa antara 2002 hingga 2020, Indonesia kehilangan sekitar 9,7 juta hektare hutan primer. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi kedua setelah Brasil, yang kehilangan 26,2 juta hektare. Hilangnya hutan bukan hanya memperbesar emisi karbon, tetapi juga mengancam keberlangsungan masyarakat adat yang kehidupannya bertumpu pada hutan.
Sebagai respon global, lahirlah mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+) di bawah naungan UNFCCC, yang kemudian diadopsi secara resmi melalui Warsaw Framework pada COP19 tahun 2013. REDD+ tidak sekadar mencegah deforestasi dan degradasi, tetapi juga mencakup konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta peningkatan cadangan karbon. Indonesia termasuk pionir dengan meluncurkan Strategi Nasional REDD+ sejak 2012, dan menerapkan Forest Reference Emission Level (FREL) untuk memantau capaian pengurangan emisi.
Secara global, tren kehilangan hutan memang menurun, dari rata-rata 7,8 juta hektare per tahun di dekade 1990-an menjadi 4,7 juta hektare per tahun di 2010–2020. Namun, angka tersebut masih jauh dari cukup untuk menjaga target Paris Agreement yang berupaya menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5°C. Dalam situasi ini, negara-negara berhutan tropis, termasuk Indonesia, melihat REDD+ sebagai instrumen penting untuk menghubungkan konservasi hutan dengan insentif finansial melalui mekanisme pasar karbon internasional.
Namun, muncul pertanyaan mendasar: siapa sebenarnya yang paling mendapat manfaat dari REDD+? Selama berabad-abad, masyarakat adat menjaga hutan dengan kearifan ekologis tradisional. Penelitian menunjukkan bahwa wilayah adat memiliki tingkat deforestasi jauh lebih rendah dibanding wilayah hutan negara. Praktik agroforestri, larangan musiman berburu, hingga ritual adat menjaga hutan adalah bentuk konservasi efektif. Sayangnya, kearifan ini sering diabaikan dalam skema teknokratis akuntansi karbon.
Di Indonesia, pengakuan hukum terhadap hutan adat menguat sejak putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Tetapi, implementasi di lapangan masih terbatas. Proyek REDD+ kerap gagal melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Beberapa kasus bahkan menimbulkan risiko perampasan tanah (land grabbing), marginalisasi perempuan adat, serta mekanisme pembagian manfaat yang tidak jelas.
Dalam konteks ekonomi, peluang baru hadir lewat Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) yang diluncurkan pada 2023. Nilai kredit karbon kehutanan diperkirakan mencapai miliaran dolar per tahun. Jika dikelola transparan dan adil, pasar karbon dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Namun, jika hanya dikuasai negara dan korporasi, masyarakat adat berisiko kembali diposisikan sebagai penonton pasif, diminta menjaga hutan tanpa memperoleh manfaat yang layak.
Perkembangan terbaru memberi secercah harapan. Pada 12 Agustus 2025, Kementerian Kehutanan bersama UNDP menggelar kick-off meeting penyusunan proposal tahap kedua RBP REDD+ kepada Green Climate Fund (GCF), dengan target pendanaan USD 80–90 juta (Rp1,3–1,4 triliun). Proposal ini dirancang lebih berbasis bukti, inklusif, dan berorientasi pada kondisi lapangan, termasuk integrasi isu masyarakat adat. Pada tahap pertama (2014–2016), Indonesia sukses menurunkan emisi 20,25 juta ton CO₂e yang menghasilkan pembayaran berbasis hasil sebesar USD 103,8 juta dari GCF.
Selain itu, lebih dari Rp251 miliar telah disalurkan kepada 15 provinsi melalui lembaga perantara, dengan program berdurasi 1–4 tahun. Di Kalimantan Tengah, misalnya, FGD penyusunan Rencana Aksi REDD+ Yurisdiksi pada 14 Agustus 2025 melibatkan pemerintah daerah, masyarakat adat, dan NGO. Contoh ini menunjukkan bahwa partisipasi lokal adalah kunci percepatan akses pendanaan sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi.
Namun, pembelajaran tahap pertama perlu dievaluasi serius. Pendanaan tahap kedua harus dikelola secara inklusif, dengan pengarusutamaan hak masyarakat adat dan kesetaraan gender. Perempuan adat, yang kesehariannya paling dekat dengan hutan, perlu diposisikan sebagai aktor utama, bukan sekadar penerima manfaat. Penerapan Environmental and Social Safeguards (ESS) dan mekanisme pengaduan (FGRM) melalui lembaga independen juga harus diperkuat, guna mencegah perampasan lahan dan memastikan keberlanjutan ekologi.
Mekanisme pembagian manfaat perlu dirancang transparan dan adil. Masyarakat adat harus memperoleh bagian nyata, baik melalui dana komunitas, pembayaran langsung, maupun investasi sosial untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur hijau. Lebih jauh, REDD+ perlu mengintegrasikan pengetahuan ekologis adat, sehingga skema ini tidak hanya berhenti pada penghitungan karbon, tetapi juga merawat ekologi berdasarkan budaya lokal. Manfaat non-karbon, seperti ekowisata, hasil hutan non-kayu, kewirausahaan hijau, hingga ekonomi berkelanjutan, harus menjadi bagian dari agenda, agar kesejahteraan komunitas adat tumbuh seiring tercapainya mitigasi iklim.
Akhirnya, masa depan REDD+ di Indonesia tidak ditentukan hanya oleh besarnya devisa dari pasar karbon global atau jumlah karbon yang berhasil diserap. Legitimasi sejati REDD+ bergantung pada keadilan sosial: apakah masyarakat adat diposisikan sebagai subjek, bukan sekadar objek. Jika keadilan ini diwujudkan, REDD+ dapat menjadi instrumen yang bukan hanya menahan laju deforestasi, tetapi juga memulihkan relasi antara manusia, hutan, dan iklim. Jika tidak, REDD+ hanya akan menjadi ilusi hijau yang memperpanjang marginalisasi masyarakat adat di tengah krisis ekologis.
***
Aditya Pratama P., Mahasiswa Universitas Indonesia.





Tinggalkan komentar